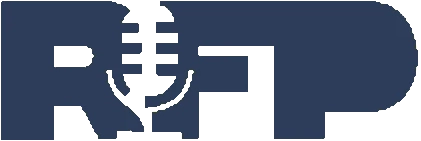Perdebatan tentang posisi Polri di bawah presiden atau kementerian meminggirkan persoalan lebih penting: bagaimana kekuasaan koersifnya dikendalikan.
Jakarta, 31 Januari 2026 – Pro dan kontra mengenai penempatan Kepolisian RI di bawah kementerian sama-sama sah di dalam ruang demokrasi. Perbedaan pandangan mencerminkan kegelishan tentang bagaimana kekuasaan koersif negara seharusnya diatur. Keduanya berangkat dari asumsi yang patut diuji, bukan disangkal. Dalam negara hukum, tidak ada desain kelembagaan yang kebal dari perdebatan.
Membahas kemungkinan Polri berada di bawah kementerian tidak melanggar konstitusi. Justru wacana ini menyangkut tata kelola, akuntabilitas, dan relasi kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan. Di banyak negara demokrasi, kepolisian ditempatkan di bawah kementerian tanpa kehilangan independensinya. Yang menentukan bukan semata posisi struktural, melainkan mekanisme kontrol dan pembatasan kewenangan.
Sebaliknya, mereka yang membela Polri tetap berada langsung di bawah presiden berargumen bahwa posisi saat ini memberi kelebihan berupa kohesi institusional yang mempercepat koordinasi dan menjaga stabilitas keamanan, sekaligus memungkinkan penyelarasan kebijakan pengakan hukum dengan agenda pemerintah. Namun kelebihan tersebut tidak otomatis menjawab persoalan akuntabilitas yang selama ini menjadi sorotan publik.
Belakangan, perdebatan justru menunjukkan kecenderungan menyempit. Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara terbuka menolak usulan Polri di bawah kementerian, melainkan tetap di bawah presiden. Pernyataan ini bahkan dibingkai sejalan dengan pandangan Presiden Prabowo Subianto.
Ketika sikap institusional kepolisian dilekatkan langsung dengan kehendak presiden, ruang kritik yang sah berisiko menciut. Masukan masyarakat sipil, akademikus, ataupun praktisi hukum dapat dianggap berseberangan dengan kekuasaan, bukan bagian dari evaluasi kebijakan yang wajar. Alih-alih membuka dialog substantif tentang tata kelola dan akuntabilitas, pernyataan Kapolri mencerminkan sikap defensif serta kecenderungan alergi terhadap masukan.
Yang menarik, perbincangan soal posisi kelembagaan Polri sering menjadi ramai dan hangat. Namun persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan warga, seperti kekerasan, penyiksaan, kriminalisasi, dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat, justru jarang mendapat perhatian serius. Akuntabilitas Polri masih samar, pengawasan lemah, dan mekanisme pemulihan bagi korban belum berjalan optimal. Padahal praktik-praktik kepolisian yang rawan disalahgunakan inilah yang paling langsung mempengaruhi keseharian masyarakat.
Secara historis, kepolisian Indonesia bukanlah institusi statis. Pada masa awal kemerdekaan, Polri pernah berada di bawah kementerian sebelum mengalami berbagai perubahan kelembagaan. Fakta ini menunjukkan desain kelembagaan selalu merupakan hasil pilihan politik dan konteks sosial, bukan sesuatu yang final. Memagari posisi Polri sebagai isu yang tidak boleh diperdebatkan bertentangan dengan semangat reformasi Polri itu sendiri.
Fokus utama reformasi Polri tidak boleh terjebak pada pro dan kontra posisi kelembagaan. Problem terbesar terletak pada praktik keseharian. Kepolisian adalah institusi yang paling intensi berinteraksi dengan masyarakat.
Hampir setiap orang pernah berurusan dengan polisi, dari pengurusan administrasi surat izin mengemudi hingga penangan perkara pidana. Karena itu, arsitektur kelembagaan yang hendak dibangun harus berangkat dari persoalan empiris dan pengalaman masyarakat, bukan hanya logika kekuasaan di tingkat elite.
Dalam pengalaman Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, keluhan warga soal polisi yang paling sering meliputi kekerasan, penyiksaan, kriminalisasi, penyalahgunaan kewenangan, serta sulitnya mengakses mekanisme pengaduan dan pemulihan yang independen. Sepanjang 2013 hingga 2022, LBH Jakarta mendampingi 58 korban penyiksaan, dengan 25 di antaranya korban salah tangkap atau salah hukum dan 6 anak yang berhadapan dengan hukum.
Semua pelaku adalah anggota kepolisian. Ironisnya, sebagian besar kasus tidak diiringi pertanggungjawaban hukum ataupun pemulihan yang layak bagi korban. Data tersebut sekaligus menyingkap realitas bahwa besarnya kewenangan yang dimiliki aparat belum diimbangi dengan pembatasan yang memadai. Temuan ini juga sejalan dengan berbagai studi akademik.
Egon Bittner, misalnya, menegaskan bahwa diskresi yang luas hanya dapat dibenarkan apabila disertai mekanisme pertanggungjawaban yang jelas serta dapat diuji secara terbuka. Tanpa kontrol semacam itu, kewenangan koersif berisiko bergeser menjadi instrumen penindasan (Bittner, 1970).
Kekhawatiran serupa muncul dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alih-alih memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, KUHAP baru justru menempatkan Polri sebagai penyidik utama untuk semua tindak pidana, memberikan kewenangan koordinasi dan pengawasan kepada penyidik non-Polri, serta menerima berkas perkara sebelum dilimpahkan kepada penuntut umum.
Sejumlah ketentuan KUHAP baru juga memperluas kewenangan penyidik, terutama dalam upaya paksa, tapi tidak diikuti mekanisme akuntabilitas yang memadai. Pengawasan terhadap upaya paksa masih pasif karena praperadilan hanya berjalan jika pihak yang dirugikan mengajukan permohonan. Banyak orang, terutama yang miskin dan rentan, tidak memiliki akses atau pendampingan hukum. Akibatnya, diskresi penyidik pada tahap awal proses pidana sulit dikoreksi dengan cepat dan independen.
Persoalan mendasar Polri bukan semata soal di aman ia ditempatkan, melainkan bagaimana kekuasaan koersifnya dikendalikan. Perluasan kewenangan tanpa penguatan kontrol hanya akan memperdalam masalah dan derita korban. Perdebatan kelembagaan seharusnya menjadi pintu masuk membahas desain pengawasan yang lebih efektif, bukan tujuan akhir.
Reformasi Polri harus berpijak pada kepentingan warga negara. Pertanyaan kuncinya bukan siapa atasan Polri, melainkan siapa yang efektif mengawasi dan membatasi kekuasaannya. Selama mekanisme pengawasan eksternal masih lemah dan akses keadilan bagi korban belum terjamin, perdebatan kelembagaan akan terasa hampa.
Negara hukum menuntut keberanian mengevaluasi institusi secara jujur, termasuk institusi yang memegang senjata dan kewenangan paksa. Reformasi Polri bukan soal simbol dan posisi, tapi memastikan kepolisian benar-benar bekerja sebagai pelindung warga.
Muhammad Fadhil Alfathan adalah seorang pengacara publik yang juga menjabat sebagai Direktur LBH Jakarta di periode 2024-2028.
Artikel ini telah tayang di laman opini Tempo pada tanggal 31 Januari 2026. Website Koalisi RFP baru menaikkan artikel ini pada tanggal 10 Februari 2026.
Tempo adalah salah satu grup media terkemuka di Indonesia yang didirikan pada 6 Maret 1971 oleh Goenawan Mohamad dan rekan-rekan. Berfokus pada jurnalistik mendalam, produknya mencakup majalah mingguan Tempo, koran (digital), situs web Tempo.co, TV Tempo, serta penerbitan buku.